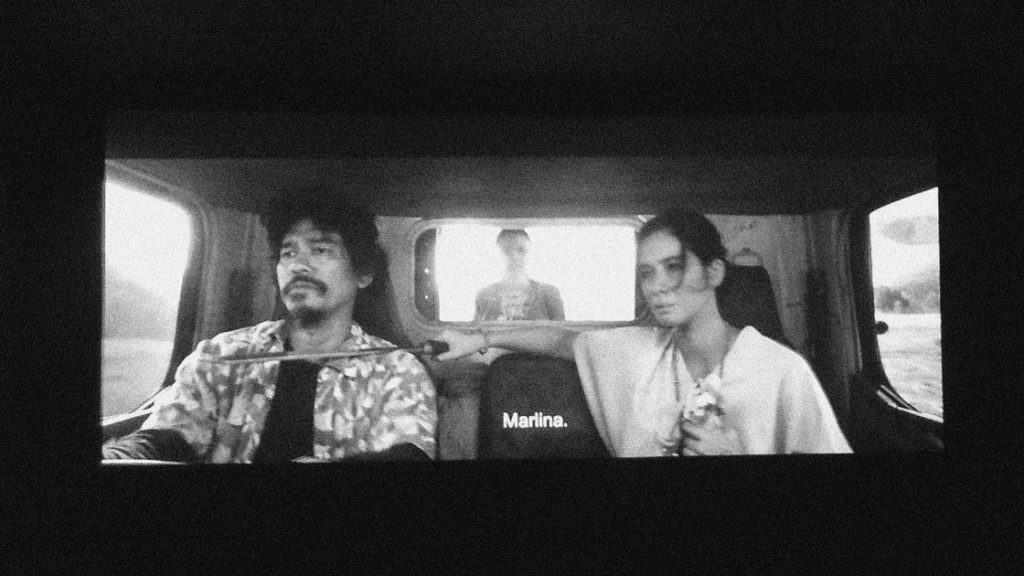Apa orang mengira dunia hanya milik lelaki? (Pramoedya Ananta Toer, 2006:435)
***
Tulisan ini akan saya mulai dengan cerita sebuah pengalaman pribadi yang dialami ketika masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Suatu sore, ketika saya sedang bersepeda sendirian untuk membeli peralatan sekolah di toko dekat rumah, seorang laki-laki yang berjalan berlawanan arah, tiba-tiba menyentuh punggung lalu memegang, menekan, dan meremas payudara kanan saya. Ia kemudian berlari secepat kilat, menjauh. Seketika saya hanya berhenti, diam, tidak berbuat apa-apa karena tidak tahu apa maksud kejadian yang baru saja menimpa. Saya hanya menoleh ke belakang, melihat lelaki itu berlari mundur sambil tertawa menghadap ke arah saya.
Bertahun saya pendam kejadian itu sendiran, karena benar-benar tidak tahu apa maksudnya. Sampai suatu saat, ketika saya sudah SMA, membaca salah satu artikel di majalah remaja mengenai kekerasan seksual, saya tersadar bahwa yang saya alami beberapa tahun silam itu adalah sebuah kekerasan seksual.
Begitu marah saya tehadap diri sendiri, merasa menjadi orang yang paling bodoh karena hanya diam dan tidak tahu apa-apa. Sementara, raut wajah licik si lelaki jahanam terus terngiang di kepala saya. Raut wajah yang tidak pernah terlupakan oleh saya sampai sekarang, dua puluh tahun kemudian.
Begitu besar efek psikologis dari pengalaman menjadi korban kekerasan seksual, dari merasa menjadi diri paling bodoh dan teror bayangan wajah licik. Pernah juga saya merasa, perbedaan ukuran pada kedua payudara saya adalah akibat dari kekerasan yang saya alami. Sampai akhirnya saya membaca artikel lain tentang anatomi tubuh, bahwa ada sebuah penelitian yang mengatakan mungkin saja terjadi perbedaan ukuran atau keadaan secara alamiah pada organ-organ tubuh manusia yang berjumlah dua. Seketika efek psikologis yang saya rasakan berkurang walaupun tidak sepenuhnya hilang.
Beberapa kali juga saya mendengar kisah-kisah teman lainnya yang mengalami hal serupa, entah disentuh bokong, vagina, atau mengalami cat calling, dan street harassment lain.
Bahwa perkosaan adalah kekerasan seksual paling berat yang dialami oleh perempuan, dan pelakunya dihukum maksimal, ya itu harus. Tidak ada kompromi. Ada undang-undang yang mengatur.
Sedangkan street harassment, yang mungkin saja, merupakan pelecehan ringan dibandingkan dengan perkosaan, tetap merupakan kekerasan. Kekerasan yang, sering dialami oleh perempuan—lumrah terjadi, menjadi hal yang sangat dilematis untuk ditanggapi.
Bukan maksud saya membandingkan, tetapi street harassment menjadi catatan penting bagi saya pribadi.
Jalanan, menjadi tempat paling tidak aman bagi perempuan. Segala pelecehan bahkan kekerasan terjadi pada perempuan.
Saya sempat menanyai beberapa teman lelaki, apakah mereka pernah siul-siul atau godai perempuan? Lalu pertanyaan itu berlanjut pada, apakah mereka sadar bahwa perbuatan itu termasuk pelecehan seksual?
Jawaban-jawaban yang saya dapat dari mereka tidak ada yang serius, bahkan ada yang menjawab di luar konteks. Dari situ saya berendapat bahwa, tubuh perempuan; wajah perempuan; pakaian perempuan, bagi sebagian laki-laki adalah komedi, segala sesuatu yang menempel pada tubuh perempuan hanyalah sebuah banyolan. Tidak pandang bulu. Bahkan seorang perempuan berhijab saja tetap menjadi obyek kekonyolan. Lalu apa yang salah?
Salah lo jadi perempuan!
Bagi sebagian besar orang, yang salah tetap si perempuan. Bahkan ironinya, sesama perempuan saling menyalahkan, “Salahnya pakai baju seksi,” atau “Salahnya tidak berada di gerbong khusus perempuan,” —bahkan memilih transportasi publik saja tetap berdasarkan gender, “Lihat saja tatonya, pantas kalau dia mengalami itu,” atau “salahnya salahnya” yang lain. Dengan sedih harus saya akui, perempuan memang suka berkompetisi dengan sesama perempuan.
Bagi sebagian perempuan biasanya tidak bisa menanggapi street harassment yang dialami. Biasanya kaget, atau bingung, atau takut. Mereka merasa ada risiko buruk yang bisa saja terjadi pada diri sendiri jika meladeni (melawan) gangguan itu. Padahal, itu hal yang salah.
Ini harus dilawan!
Dengan membiarkan, para pelaku street harassment dan masyarakat tidak sadar bahwa siulan-siulan atau godaan-godaan atau tatapan mesum terhadap perempuan itu membuat seorang perempuan merasa tidak nyaman. Sekali lagi: TIDAK NYAMAN. Itu adalah pelecehan. Sekali lagi dengan huruf tebal: PELECEHAN. Bahwa salah besar jika tubuh perempuan hanyalah menjadi obyek komedi atau nafsu seksual laki-laki.
Bayangkan ibu anda, yang selama sembilan bulan mengandung, lalu anda dilahirkan melalui vagina atau perut yang disobek dalam operasi. Lalu ibu anda memberikan hidup pertama kepada anda melalui asi yang keluar dari payudara, ketika kalian—lelaki— berniat melakukan street harassment terhadap perempuan. Bayangkan ibu anda mengalami hal itu di jalan.
Atau, ya menjadi manusia yang menghargai manusia lain. Itu saja!
***
Pendidikan seks harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya sejak dini. Harus diakui, saya tidak mendapatkan hal itu dari kedua orang tua saya. Saya harus mengalami sendiri hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, untuk saya belajar, dan itu salah. Bahwa tidak ada orang lain yang boleh menyentuh bagian tubuh selain kita sendiri. Agar mereka paham bahwa tubuh adalah otoritas pribadi setiap manusia. Jangan lagi menganggab tabu.
Sekali lagi, street harassment adalah kekerasan dan kekerasan harus dilawan. Kadang kala, jika dirasa keadaan aman, perempuan harus berani bertolak pinggang dan menatap tajam ketika disiuli oleh laki-laki; bahwa harus teriak sekencang-kencangnya agar orang lain mendengar lalu mengejar lelaki yang baru saja menyentuh tubuh perempuan, karena kadang kita perlu adanya pengadilan masyarakat dalam skala kecil; dan setiap perempuan sudah sepatutnya menyimpan air cabai atau merica dalam botol kecil yang siap disemprotkan ke mata laki-laki yang berusaha melakukan pelecehan atau kekerasan. Berjaga-jaga atas segala kemungkinan buruk. Namun, kita semua tentunya berharap itu tidak terjadi.
Saya sengaja menulis dan menceritakan kejadian buruk yang saya alami ini, karena dengan tulisan saya melawan. Menulis adalah sebuah keberanian. Saya juga berharap ada perempuan lain yang berani melakukan hal serupa; melakukan perlawanan, apapun caranya.
Ini bukan soal tubuh perempuan, bukan soal hijab perempuan, bukan soal pakaian perempuan, bukan soal tato perempuan, tetapi ini adalah penyakit yang berada di dalam isi kepala laki-laki.
Bagi saya, seorang Pramoedya Ananta Toer adalah seorang feminis. Dalam buku Jejak Langkah dengan jelas ia menulis, “Aku tidak menyukai patriark, siapapun orangnya.” Tulisannya selalu berbicara tentang perempuan kuat yang melawan dalam kelemahannya. Dalam Tetralogi Pulau Buru ia mengisahkan perempuan perkasa bernama Nyai Ontosoroh; ia juga secara khusus mempersembahkan cerita Gadis Pantai untuk neneknya; bahkan dengan lugas ia memuji R.A Kartini dalam Panggil Aku Kartini Saja; dan buku-buku lainnya.
Karena menjadi feminis tidak harus menjadi perempuan. Feminis untuk ibu pertiwi.